Saya menulis ruangan ini dari kapal terbang, dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia, ke rumah baru saya, Wellesley, Mass. Saya berada di tempat duduk yang selesa, dan saya tidak sabar untuk kembali ke keluarga saya. Namun, kira-kira 12 jam yang lalu, saya menderita, dikurung di dalam bilik tahanan oleh “polis agama” Malaysia.
Kisahnya bermula beberapa bulan yang lalu, ketika Islamic Renaissance Front, organisasi reformis, sebuah organisasi Muslim progresif di Malaysia, mengundang saya untuk memberikan siri ceramah mengenai Islam, akal, dan kebebasan. Kumpulan ini pernah menjadi tuan rumah saya tiga kali sebelum ini dalam lima tahun yang lalu untuk acara serupa dan juga menerbitkan versi bahasa Melayu buku saya “Islam Tanpa Ekstrem: Kes Muslim untuk Kebebasan.” Saya gembira kerana berpeluang mengunjungi Malaysia lagi.
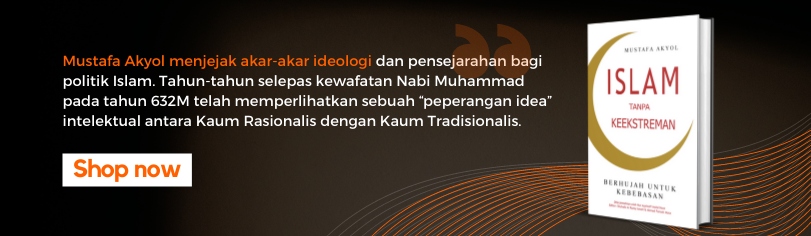
Saya tiba di Kuala Lumpur pada 22 September 2017. Keesokan harinya saya memberi kuliah pertama saya mengenai penindasan teologi rasional oleh dogmatisme pada awal Islam, yang menyatakan bahawa “intellectual suicide” ini masih menghantui peradaban Muslim.
Ceramah kedua adalah mengenai topik yang lebih kontroversial: murtad dari Islam. Saya berpendapat bahawa umat Islam harus menegakkan kebebasan hati nurani, sesuai dengan tulisan Quran “Tidak ada paksaan dalam agama.” Saya mengatakan bahawa murtad tidak boleh dihukum mati, seperti di Arab Saudi, atau dengan “pemulihan”, seperti yang berlaku di Malaysia. Pengamalan Islam mestilah berdasarkan kebebasan, bukan paksaan, dan pemerintah tidak boleh menjaga agama atau moral.
Ternyata yang harus anda lakukan ialah bercakap mengenai polis dan mereka akan muncul.
Pada akhir ceramah saya, sekumpulan lelaki berwajah serius datang ke dewan kuliah dan menunjukkan lencana yang menunjukkan bahawa mereka adalah “pegawai penguat kuasa agama.”
“Kami mendengar bahawa anda baru saja memberi ceramah yang tidak sah mengenai agama,” kata salah seorang lelaki itu. “Dan kami mendapat aduan mengenainya.” Mereka membawa saya ke bilik lain, memotret saya, dan mengajukan soalan mengenai ucapan saya.
Setelah selesai menyoal, mereka menyerahkan sehelai kertas dengan tulisan Melayu di atasnya dan memberitahu bahawa saya tidak boleh bercakap lagi tanpa kebenaran yang betul. Mereka juga memperingatkan saya dari ceramah saya yang direncanakan berikutnya, yang akan membahas buku terbaru saya, “Yesus Islam: Bagaimana Raja Yahudi Menjadi Nabi Umat Islam.”
“Kami mendengar bahawa anda akan bercakap mengenai persamaan antara Islam, Yahudi, dan Kristian,” kata seorang pegawai. “Kami tidak suka perkara seperti itu dibicarakan.” Kemudian mereka pergi.
Selepas semua ini, saya berunding dengan tuan rumah saya, dan kami memutuskan untuk membatalkan kuliah terakhir. Saya menganggap itu adalah akhir dari masalah ini dan pergi membeli hadiah untuk isteri dan anak-anak saya.
Pada suatu hari, saya pergi ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur untuk memulakan perjalanan selama 30 jam kembali ke Massachusetts. Semasa saya memberikan pasport saya kepada polis sempadan, saya menyedari bahawa pengalaman saya menyinggung perasaan Islam Malaysia belum berakhir.
“Anda harus menunggu, tuan,” kata wanita yang memeriksa pasport saya. Dia memanggil beberapa pegawai polis, yang memanggil pegawai polis lain, yang membawa saya ke sebuah bilik di mana perintah penangkapan saya dibacakan kepada saya. Rupa-rupanya polis agama, yang dikenali sebagai JAWI, ingin menyoal siasat saya lagi untuk pembicaraan saya yang “tidak benar” mengenai kebebasan beragama dan telah mengeluarkan perintah penangkapan itu untuk memastikan saya tidak meninggalkan negara ini.
Saya dibawa dari lapangan terbang ke balai polis, kemudian ke balai lain. Akhirnya, saya dibawa ke ibu pejabat JAWI, di mana saya dikurung.
Untuk bersikap adil, tidak ada yang bersikap kasar kepada saya, apalagi kejam. Namun, saya merasa tertekan: Saya telah ditangkap di negara asing yang undang-undang dan bahasa mereka saya tidak faham. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku kepada saya – dan, paling menyakitkan, apabila saya melihat isteri saya, Riada, anak lelaki kami yang berusia 2 tahun, Levent, dan bayi kami yang berusia 2 bulan, Efe.
Pada waktu pagi, saya dibawa ke mahkamah Syariah, yang digunakan di Malaysia untuk mengadili masalah agama, di mana saya diinterogasi selama dua jam. Pada akhirnya, saya terkejut, saya dilepaslan. Tidak lama kemudian, saya mendapat tahu bahawa ini sangat difasilitasi oleh usaha diplomatik negara saya, Turki – dan terutama hubungan yang dilakukan oleh bekas presiden Turki, Abdullah Gul, dengan kerabat diraja Malaysia.
Kejadian ini menunjukkan kepada saya sekali lagi bahawa ada masalah besar dalam Islam hari ini: keghairahan untuk memaksakan agama, dan bukan sekadar mengemukakannya, pemikiran yang ditinggalkan oleh kebanyakan orang Kristian pada masa Inkuisisi.
Nasib baik, ada penawar dalam Islam untuk masalah ini. Salah satu daripadanya adalah ayat Al-Quran yang pegawai JAWI berulang kali memarahi saya kerana saya dengan berani membaca: “Tidak ada paksaan dalam agama.”
Sebenarnya, tradisi umat Islam arus perdana, yang mencerminkan konteksnya yang tidak liberal, tidak pernah menghargai sepenuhnya kebebasan yang ditunjukkan oleh ayat ini – dan yang lain dengan mesej yang serupa. “Ayat” tanpa paksaan “adalah masalah bagi para pentafsir yang paling awal,” seperti yang dicatat oleh Patricia Crone, seorang sarjana sejarah Islam. “Dan mereka bertindak balas dengan menafsirkannya secara terhad.” Ayat itu dinyatakan “dibatalkan,” atau ruang lingkupnya terbatas secara radikal.
Ini masih jelas dalam kurungan yang terlalu kerap dimasukkan ke dalam terjemahan ayat. “Tidak akan ada paksaan dalam agama (untuk menjadi seorang Muslim).” Saya tahu bahawa terjemahan Saudi menambahkan kata-kata tambahan itu pada akhirnya. Sekarang saya telah mengetahui bahawa pihak berkuasa Malaysia juga.
Mereka menambahkan ungkapan tambahan kerana walaupun mereka setuju dengan Al-Quran bahawa tidak ada seorangpun yang harus dipaksa untuk menjadi seorang Muslim, mereka berpendapat bahawa orang Islam harus dipaksa untuk mempraktikkan agama tersebut – dengan cara yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Mereka juga percaya bahawa jika umat Islam memutuskan untuk meninggalkan agama mereka, mereka mesti dihukum kerana “murtad.”
Salah seorang pegawai di perbicaraan mahkamah Syariah Malaysia saya dengan bangga memberitahu saya bahawa semua ini dilakukan untuk “melindungi agama.” Tetapi saya mempunyai pesan penting untuknya (yang saya tidak ucapkan pada masa itu): Dengan pihak pegawai agama, pihak berkuasa tidak benar-benar melindunginya. Mereka hanya melemahkan masyarakat mereka, membangkitkan umat islam yang munafik, dan menyebabkan banyak orang kehilangan kepercayaan atau tidak lagi menghormati Islam.
Saya memahami bahawa semasa saya ditahan di ibu pejabat JAWI, mendengar bacaan Al-Quran yang kuat dari bilik sebelah. Saya mendengar Al-Quran dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya, ia terdengar seperti suara penindas. Tetapi saya tidak menyerah pada kesan itu. “Saya mendengar anda dan saya percaya kepada anda, Tuhan,” kata saya sambil berdoa, “walaupun orang fanatik ini bertindak atas nama anda.”
Artikel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dari tulisan asal dalam bahasa Inggeris. Klik di sini untuk tulisan asal.





